Contohnya bisa kita lihat dari banyak generasi muda hari ini yang tetap beragama secara administratif, tapi merasa jauh secara emosional. Misalnya, ikut salat atau misa rutin, tapi merasa kosong; atau mengisi kolom agama di KTP, tapi bingung saat ditanya, “Apa nilai tertinggimu sebagai manusia?”
Karen Armstrong, sejarawan agama yang banyak menulis lintas tradisi, mengingatkan bahwa sejak awal, agama bukan sekadar dogma, melainkan praktik transformasi batin. Dalam The Case for God (2009),
Armstrong menjelaskan bahwa spiritualitas sejati berakar pada welas asih, keterhubungan dengan sesama, dan keheningan kontemplatif. Tapi dalam masyarakat yang serba cepat dan digital, dimensi itu kerap hilang. Agama bisa jadi ramai, tapi keheningan batinnya menghilang.
Misalnya, kita lihat gerakan amal dan kemanusiaan kadang lebih ramai di kalangan komunitas non-agamis atau independen, padahal akar agama justru mengajarkan welas asih. Atau banyak yang aktif dalam kegiatan keagamaan, tapi merasa kewalahan mengelola emosi, trauma, atau rasa bersalah—karena tidak ada ruang dialog yang cukup aman untuk membicarakan itu.
Byung-Chul Han, dalam tulisannya The Disappearance of Rituals (terbit 2019, versi Inggris 2020), mengkritik bagaimana budaya modern telah mengikis struktur simbolik yang menyatukan makna hidup manusia. Ia menyebut bahwa kita kehilangan ritus, kehilangan kedalaman. Segalanya kini diburu dalam bentuk visual, interaktif, dan terfragmentasi. Han menyiratkan bahwa dalam masyarakat digital, agama pun bisa terdorong untuk menjadi “konten” — bukan lagi ruang hening dan pencarian.
Contohnya bisa kita lihat dari bagaimana tradisi seperti mudik, buka puasa bersama, atau Natal jadi ajang foto dan postingan. Simbol tetap ada, tapi makna batinnya kerap tertinggal. Kita rayakan “momen”, tapi kehilangan “kedalaman”.
Fenomena ini terasa di berbagai belahan dunia, termasuk di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika Latin. Ketika agama bertemu dengan sistem kapitalisme dan budaya internet, banyak praktik spiritual mengalami transformasi bentuk. Ritual tetap ada, institusi tetap jalan, tapi esensi sering bergeser ke arah simbolik, sosial, bahkan performatif. Identitas keagamaan hadir sebagai ekspresi luar, tapi belum tentu menembus ke wilayah batin yang paling sunyi.
Zygmunt Bauman menyebut bahwa dalam masyarakat cair, agama pun menjadi pilihan yang bersifat konsumtif. Gagasan tentang masyarakat cair (liquid modernity) dikembangkan Bauman sejak awal 2000-an — terutama dalam bukunya Liquid Modernity (2000), Liquid Love (2003), dan Liquid Fear (2006). Orang bisa “beralih” dari satu komunitas ke komunitas lain sesuai kenyamanan. Tapi hal ini tidak selalu menyelesaikan pencarian makna — justru bisa memperpanjang fase “pencarian tanpa kedalaman.”
Contoh konkretnya, seseorang bisa ikut pengajian atau retret spiritual satu bulan, lalu pindah ke komunitas yoga atau meditasi digital berikutnya. Pencarian makna jadi seperti “window shopping” — cepat ganti, tapi tak pernah menetap.
Dalam konteks ini, kita tidak sedang menyalahkan agama—melainkan sedang melihat bahwa manusia modern butuh cara baru untuk berelasi dengan keyakinan, nilai, dan spiritualitas. Bukan sekadar mengikuti, tapi mengalami. Bukan hanya tahu, tapi merasa. Hanya hafal, tapi terhubung.
Krisis spiritualitas modern bukan karena agama hilang, tapi karena hubungan manusia dengan dimensi spiritualnya menjadi retak, terpisah, atau terdistraksi. Dan ketika manusia kehilangan kontak dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya, dia kehilangan arah—tak lagi tahu bagaimana mengartikan hidup, penderitaan, atau tujuan keberadaannya.
🌍 Ketika Bumi Menjerit dan Manusia Masih Mengejar Pertumbuhan
Di dunia yang katanya semakin modern dan canggih, satu hal terasa makin nyata: bumi sedang sakit.
Suhu global meningkat, laut naik, cuaca makin ekstrem. Hutan terbakar, es mencair, dan spesies punah tiap hari. Tapi ironisnya, di tengah semua ini, manusia masih bicara soal pertumbuhan ekonomi—seakan semua itu tidak punya batas.
Inilah wajah nyata dari krisis abad ini: ketika planet kita yang satu-satunya ini mulai sekarat, sistem ekonomi kita justru terus mendorong konsumsi dan produksi tanpa henti. Seolah pertumbuhan adalah kebenaran absolut, dan segala hal lain—termasuk ekosistem—hanya pelengkap.
Jason Hickel, ekonom dan penulis buku Less Is More (2020), menyebut bahwa krisis iklim bukan semata-mata soal emisi karbon, tapi soal sistem ekonomi yang memang dibangun untuk tumbuh terus-menerus. Ia menyebut sistem ini sebagai “engine of extraction”—mesin yang tidak bisa hidup tanpa mengambil terus dari alam.
Menurut Hickel, pertumbuhan ekonomi di dunia saat ini tidak hanya menciptakan ketimpangan sosial, tapi juga mempercepat kehancuran ekologis. Ia mengusulkan pendekatan baru yang disebut “degrowth” — bukan berarti stagnasi, tapi pertumbuhan yang tidak lagi bergantung pada eksploitasi sumber daya alam.
Naomi Klein, jurnalis dan aktivis lingkungan asal Kanada, dalam bukunya This Changes Everything (2014), bahkan menyebut bahwa sistem kapitalisme pasar bebas adalah lawan langsung dari solusi iklim. Karena selama keuntungan jadi tujuan utama, maka eksploitasi dan polusi akan terus dijustifikasi sebagai “efisiensi”.
Masalahnya, dalam banyak kebijakan pemerintah dan narasi bisnis, pertumbuhan masih dijadikan tolok ukur keberhasilan. Produk domestik bruto (PDB) dianggap sakral. Bila naik: sukses. Bila turun: panik. Padahal, PDB bisa naik karena penebangan hutan, ekspansi tambang, atau pembangunan beton yang merusak ruang hidup—apakah itu bisa dibilang kemajuan?
Bruno Latour, filsuf dan sosiolog Perancis, menyebut bahwa manusia modern hidup dalam ilusi bahwa kita terpisah dari alam. Padahal, realitanya kita hidup di dalam ekosistem, bukan di atasnya. Dalam esainya Facing Gaia (2017), Latour mengajak kita berhenti bersikap seperti penguasa bumi, dan mulai belajar sebagai bagian dari kehidupan itu sendiri.
Contoh krisis ini bukan lagi hal yang jauh. Indonesia sudah merasakannya:
- Banjir Jakarta makin parah
- Cuaca makin tak menentu
- Wilayah pesisir seperti Demak dan Tegal mulai tergenang air laut secara permanen
- Petani gagal panen karena perubahan musim
- Polusi udara Jakarta jadi salah satu yang terburuk di dunia
Di sisi lain, narasi “green economy” atau “hijau berkelanjutan” seringkali hanya jadi topeng. Banyak korporasi bicara soal sustainability, tapi tetap membuka lahan sawit, membangun kawasan industri, atau mendorong konsumsi besar-besaran lewat iklan yang membius. Kita sering ganti kemasan, bukan sistemnya.
Bumi tidak sedang butuh kita jadi sempurna. Tapi bumi butuh manusia yang sadar bahwa waktu kita makin sempit. Butuh generasi yang berani mempertanyakan: apakah pertumbuhan ekonomi yang kita puja itu masih layak diperjuangkan, kalau harus menghancurkan rumah tempat kita hidup?
Catatan : “Artikel ini merupakan bagian dari seri Trend Perubahan Dunia Baru, yang dipublikasikan secara bertahap di blog Rooma21.com.”
Selanjutnya, baca artikel berjudul: “Dunia 2025: Di Persimpangan Perubahan Sosial dan Ekonomi.”
Visit www.rooma21.com: kami lebih dari sekadar platform properti, rumah ideal dimulai dari referensi yang tepat, rooma21.com: referensi real estate, mortgage & realtor di Indonesia, hadir untuk millenial dan genzie mewujudkan gaya hidup impian.




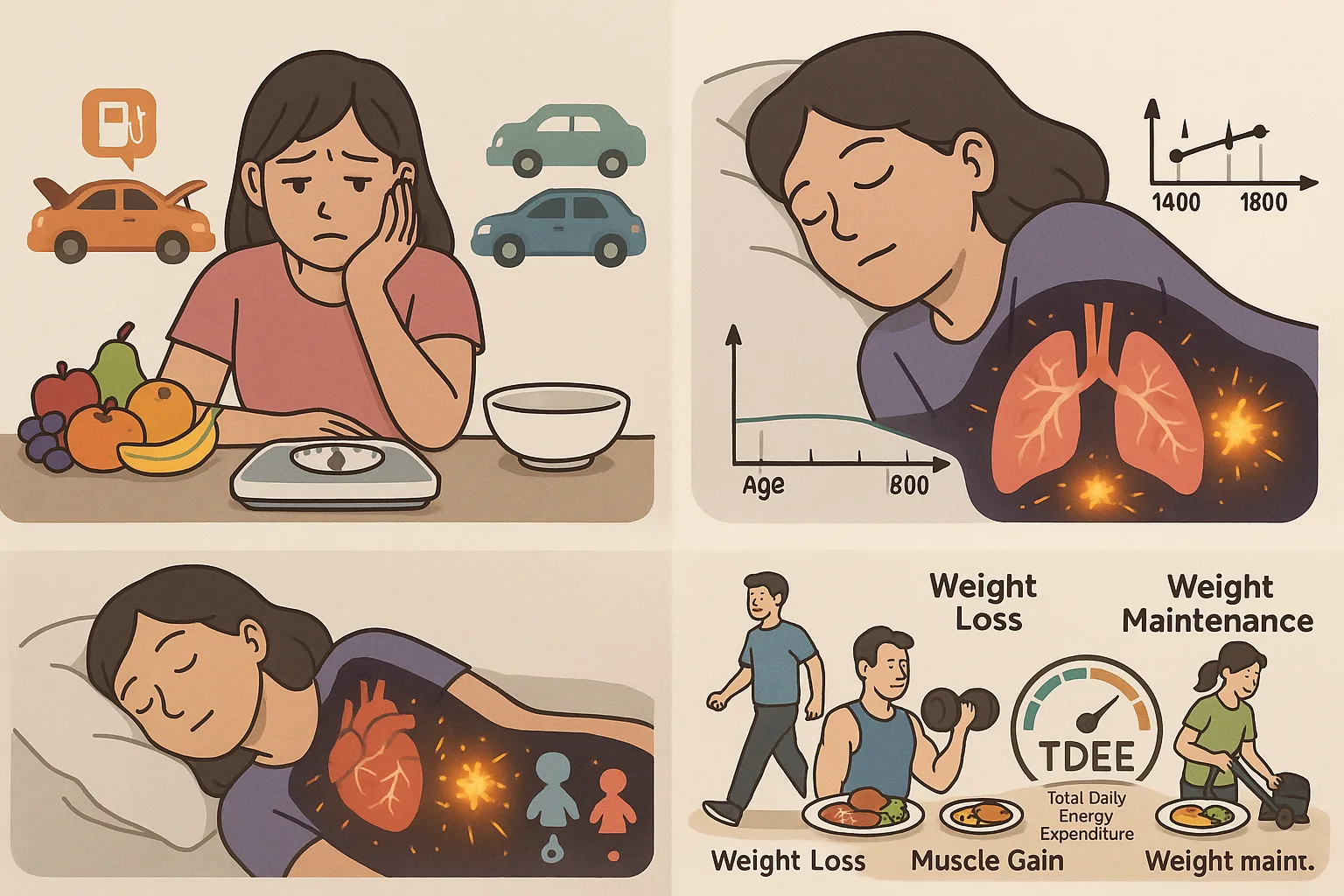


Komentar