Rooma21.com, Jakarta – Kapitalisme global tampaknya sudah menang. Sistem ini menciptakan pertumbuhan, efisiensi, inovasi, dan mengubah cara hidup manusia dengan kecepatan luar biasa. Tapi kemenangan ini bukan tanpa masalah — karena yang mendominasi bukan sekadar kapitalisme biasa, tapi bentuk ekstremnya: kapitalisme neoliberal. Sistem yang menjadikan produktivitas dan konsumsi sebagai pusat kehidupan, dan menilai segalanya lewat angka, keuntungan, dan efisiensi.
Sistem ini menciptakan pertumbuhan, efisiensi, inovasi, dan mengubah cara hidup manusia dengan kecepatan luar biasa. Teknologi menjangkau semua sisi hidup, ekonomi tumbuh di banyak negara, dan peluang terbuka lebar. Tapi di balik semua kemajuan ini, makin banyak orang justru merasa kosong.
Di balik semua kemajuan itu, makin banyak orang justru merasa kosong.
Generasi muda, bahkan yang berpendidikan tinggi dan bekerja di perusahaan besar, banyak yang merasa hidupnya datar. Mereka kelelahan, kehilangan arah, dan merasa seperti hidup dalam mode autopilot. Di tengah semua kesibukan dan keterhubungan, justru muncul perasaan hampa yang susah dijelaskan.
Salah satu yang mengangkat hal ini adalah Byung-Chul Han, filsuf kontemporer asal Korea Selatan yang kini mengajar di Jerman. Lewat bukunya The Burnout Society, ia menggambarkan masyarakat modern sebagai “masyarakat kelelahan”. Kita hidup dalam budaya yang mendorong individu untuk terus-menerus jadi versi terbaik dari diri sendiri. Bahkan saat istirahat pun, banyak orang merasa bersalah kalau tidak produktif. Liburan pun berubah fungsi—bukan untuk beristirahat, tapi untuk recharge agar bisa kerja lebih keras. Tekanan bukan lagi datang dari luar, tapi dari dalam diri sendiri. Kita jadi capek bukan karena disuruh, tapi karena terus menekan diri agar tetap relevan, berprestasi, dan tidak tertinggal.
Kondisi ini nyambung dengan gagasan dari David Graeber, seorang antropolog asal Amerika Serikat dan profesor di London School of Economics (sebelum wafat di 2020). Dalam bukunya Bullshit Jobs, ia menjelaskan fenomena banyaknya pekerjaan modern yang dianggap tidak berguna oleh pelakunya sendiri. Pekerjaan itu tetap dijalani demi gaji, status, dan karena sistem menuntut begitu. Banyak orang bekerja dari Senin sampai Jumat tanpa rasa memiliki terhadap apa yang dikerjakannya. Mereka sibuk, tapi tidak merasa hidup. Ini menciptakan alienasi: keterputusan antara energi yang dikeluarkan dengan makna yang didapat.
Sementara itu, Slavoj Žižek filsuf dan kritikus budaya asal Slovenia yang dikenal karena gaya bicaranya yang eksplosif dan pemikiran tajam soal ideologi mengingatkan bahwa kapitalisme punya kemampuan menyerap kritik terhadap dirinya sendiri. Bahkan gerakan sosial seperti kesadaran lingkungan, inklusivitas, dan kesehatan mental bisa dijadikan alat promosi korporasi. Sistem ini tampak seolah “progresif”, padahal esensinya tetap mengejar profit. Hal ini menciptakan iklim skeptis: semua tampak sadar, tapi tidak ada yang benar-benar berubah.
Terakhir, Yuval Noah Harari, sejarawan dan penulis asal Israel yang terkenal lewat buku Sapiens dan Homo Deus, memperingatkan bahwa manusia kini berada dalam bahaya kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Kita hidup di era algoritma, di mana pilihan kita—dari apa yang dibeli, ditonton, hingga dipikirkan—semakin banyak diarahkan oleh sistem digital. Algoritma bisa mengenali emosi dan pola perilaku kita lebih dalam dari yang kita sadari sendiri. Akibatnya, manusia perlahan kehilangan agensi dan arah hidup. Kita menjadi “makhluk yang disetir”, bukan makhluk yang memilih.
Kalau kita tarik garis besar dari keempat pemikiran ini: sistem modern ini memang berhasil secara teknis—membangun ekonomi, menciptakan konektivitas, mempercepat segalanya. Tapi dalam proses itu, kita kehilangan hal yang paling dasar—makna.
Kita diajari bahwa nilai manusia diukur dari produktivitas dan konsumsi. Bahwa hidup harus selalu “naik level”. Tapi makin kita kejar semua itu, makin banyak yang kehilangan pegangan. Banyak yang merasa berhasil secara sosial, tapi gagal secara personal. Kita punya semuanya, tapi merasa tidak punya siapa-siapa. Kita merasa tidak dilihat, meski selalu tampil.
Krisis besar abad ini bukan hanya soal teknologi, lingkungan, atau ketimpangan. Tapi krisis yang lebih dalam: manusia kehilangan orientasi hidupnya. Kita tak lagi tahu kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan. Tujuan berubah jadi angka, relasi berubah jadi data, eksistensi berubah jadi konten. Inilah krisis eksistensial kolektif yang sedang membayangi dunia modern—krisis yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan update sistem, tapi butuh arah baru.
Ketika Diri Menjadi Data: Identitas Manusia di Era Digital | Kapitalisme

Kita hidup di zaman yang semuanya bisa diukur, ditampilkan, dan disimpan sebagai data. Tapi justru di saat kita paling “terlihat”, kita makin sulit mengenal diri sendiri. Identitas yang dulunya terbentuk lewat pengalaman, nilai, dan relasi mendalamhari ini dibentuk dari luar: jumlah views, likes, komentar, dan validasi digital.
Banyak orang sekarang lebih kenal versi diri mereka di Instagram dibanding versi diri di cermin. Kita jadi ahli membangun “persona”, tapi bingung saat diminta menjawab pertanyaan paling dasar: “Siapa kamu sebenarnya?”
Sherry Turkle, profesor di MIT dan penulis buku Alone Together, menyebut kondisi ini sebagai bentuk keterasingan modern. Kita selalu terkoneksi, tapi makin kesepian. Di layar, kita punya banyak interaksi. Tapi di luar itu, kita mulai kesulitan menjalin relasi yang benar-benar dalam dan hadir. Kita jadi takut pada keheningan, karena di keheningan itu kita bisa merasa hilang arah.
Tekanan untuk punya pendapat di media sosial, untuk terlihat cerdas, untuk tampil lucu, untuk selalu update — semua itu membuat identitas jadi performa. Orang merasa harus membentuk citra, bukan mencari keaslian. Kita bukan lagi menjadi, tapi membangun tampilan tentang siapa yang ingin dilihat.
Zygmunt Bauman menyebut ini sebagai bagian dari “masyarakat cair”—semua berubah cepat, termasuk cara kita memandang diri sendiri. Di era sekarang, identitas bisa berubah dalam semalam, mengikuti tren, algoritma, atau tekanan komunitas. Kita bisa ganti persona sesuai suasana. Satu sisi ini fleksibel, tapi di sisi lain, kita makin sulit menemukan keutuhan diri. Kita jadi rentan, karena fondasi personalnya rapuh.
Fenomena ini makin terasa di generasi muda Indonesia. Di Twitter dan TikTok, kita bisa lihat bagaimana “jadi sarkas” atau “jadi dark” dijadikan gaya bicara—bukan karena refleksi diri, tapi karena takut dibilang cupu. Banyak yang merasa perlu ikut arus komentar, walau nggak tahu apa yang sebenarnya dibela. Konten opini diburu, meski kadang dibuat hanya demi validasi atau naik engagement. Di sisi lain, tekanan untuk jadi relatable bikin orang menghapus sisi asli mereka—takut beda, takut nggak lucu, takut dianggap terlalu serius.



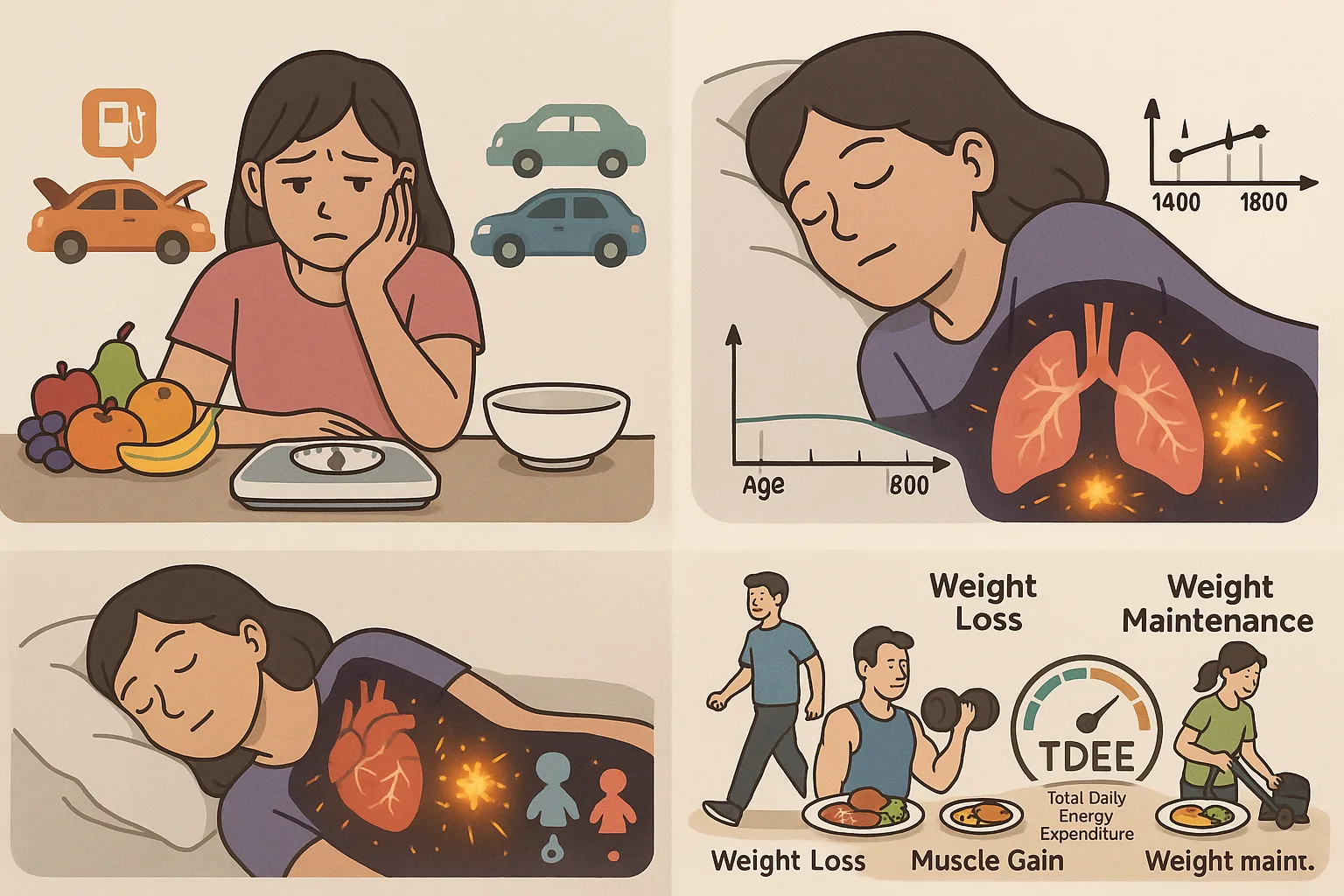


Komentar